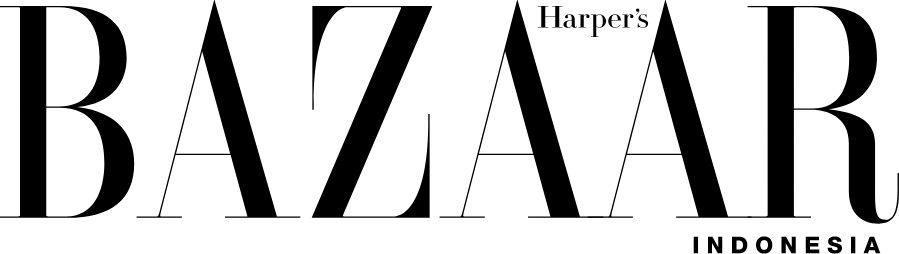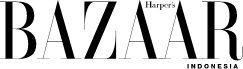E Pluribus Unum, “Dari banyak, menjadi satu.” Sebuah semboyan tentang persatuan nasional yang terdengar birokratis, terukir di luar Terowongan Midtown. Bazaar melihatnya melalui jendela belakang taksi, buram karena teriknya musim panas kota dan langsung teringat kebalikannya: E Unibus Pluram, yang kebetulan merupakan judul esai karya David Foster Wallace. Ditulis pada tahun 1993, beberapa tahun sebelum ia menerbitkan Infinite Jest, novel ambisiusnya yang dianggap sebagai calon karya agung Amerika, esai ini mengeksplorasi penolakan generasi baru terhadap ironi dalam sastra dan seni, serta peralihannya menuju pandangan budaya yang lebih tulus dan lugas.
BACA JUGA: Perkembangan Dunia Virtual yang Semakin Sempurnakan Sesi Berbelanja Online
Melalui pendekatan ini, David Foster Wallace mengharapkan visi yang lebih bersatu, sebagai lawan dari keragaman ide dan interpretasi yang terbuka. Ia mengkhawatirkan dampak reproduksi massal dan justru merangkul ekspresi emosi. Inilah semangat dari New Sincerity Movement saat itu, dan kini, Bazaar melihat kaitan yang sangat jelas dengan dunia mode.
Sejak E Unibus Pluram kembali terlintas dalam benak, Bazaar mulai menghubungkan semangat zaman fashion saat ini dengan prediksi tren David Foster Wallace tentang makna baru dari “keren” tiga dekade lalu. “Para pemberontak baru,” tulis David Foster Wallace dalam esainya, “mungkin adalah mereka yang berani dianggap membosankan, menerima ejekan, senyum sinis, lirikan meremehkan, atau sindiran dari para ironis berbakat yang akan berkata: "duh, betapa membosankan.” Seruan David Foster Wallace agar generasi baru lebih berani menghadapi cibiran dapat terlihat dalam karya para desainer paling diperbincangkan saat ini.
Pikirkan bagaimana mode mewah telah berubah selama 20 tahun terakhir, dari Gucci era Tom Ford yang penuh sensualitas, menuju Gucci era Alessandro Michele yang eksentrik; dari Balenciaga rancangan Nicolas Ghesquière yang futuristik dan elegan, ke Balenciaga era Demna yang dekonstruktif. Kedua contoh ini menyoroti pergeseran gaya berpakaian yang nyata, dari Postmodernisme menuju New Sincerity.
“Pemberontak baru” versi David Foster Wallace tidak begitu berbeda dari sosok yang selama ini menjadi muse abadi dunia fashion: si visioner yang disalahpahami, perancang yang menolak norma. David Foster Wallace ingin terlihat keren dengan caranya sendiri: bukan melalui sikap acuh, melainkan melalui keterlibatan emosional yang nyata, bahkan menyakitkan. Jika mengikuti logikanya, Gucci versi Tom Ford dan Balenciaga versi Nicolas Ghesquière mewakili semangat postmodernis. Sebaliknya, karya para penerus mereka hadir dengan ketulusan atau setidaknya dirancang agar terlihat tulus. Seperti rantai kacamata di koleksi Gucci era Michele atau dad sneakers dari Balenciaga versi Demna. Mereka tampak tulus karena meniru gaya orang-orang biasa: nenek-nenek dengan kacamata baca atau ayah-ayah dengan sepatu ortopedi yang kikuk.
Dalam pergeseran dua dekade ini, arketipe fashion berubah dari yang tak terjangkau menjadi sangat terjangkau, dari power suit dan sandal berplatform tinggi bergaya robotik, menjadi kacamata bifokal rancangan desainer dan sepatu ortopedi tebal. Paradoks yang sama juga menggerakkan banyak pergerakan mode paling menarik saat ini. Ketulusan telah menjadi sikap baru dalam dunia fashion, bukan meskipun ia rumit, tetapi karena kerumitannya.

Fashion memiliki kemampuan unik untuk melontarkan lelucon. Lihat saja koleksi couture terakhir Demna untuk Balenciaga awal bulan ini. Dalam koleksi tersebut, ia mengungkapkan konsep utama di balik siluet-siluetnya yang sering memicu kegaduhan di rumah mode Paris itu: pembentukan identitas melalui bentuk-bentuk “normcore” yang dilebih-lebihkan, seperti sneakers dan hoodie. Penyebaran tren seperti ini meniru gagasan “dari satu menjadi banyak” dalam E Unibus Pluram.
Namun, couture menyajikan argumen tandingan. Bagaimana jika fashion justru merayakan keterampilan dan tradisi selama pekan couture? Koleksi couture musim gugur 2025 dan peragaan busana pria musim semi 2026 mengemukakan hal ini dengan lebih meyakinkan dari sebelumnya: bahwa fashion hari ini bukan hanya secara tulus menyampaikan emosi, tetapi juga berani menjadikan artifisialitas sebagai medium untuk menghadirkan perasaan. Fashion dapat membangkitkan emosi justru karena ia merupakan konstruksi, bukan meskipun bisa direproduksi, tetapi karena kemampuannya diciptakan. Bentuk atau siluet baru adalah inovasi yang menantang cara kita berpakaian sehari-hari. Saat ini, kita tidak sekadar menyaksikan gelombang new sincerity dalam dunia mode; kita melihat industri ini sedang bergulat dengan makna ketulusan itu sendiri.
Ketika Glenn Martens mempersembahkan koleksi couture pertamanya untuk Maison Margiela pada musim gugur 2025, dunia fashion seakan menahan napas. Akankah ia terjatuh dalam sekadar penghormatan, atau justru menghancurkan stigma sepenuhnya? Jawabannya berada di antara keduanya dan justru karena itulah koleksi ini berhasil. Terdapat gaun-gaun remuk dan kusut (dengan tekstur metalik teroksidasi yang tampak lebih seperti hasil penggalian arkeologis ketimbang jahitan), namun kembalinya elemen topeng dalam koleksi ini menjadi penanda terkuat. Topeng-topeng tersebut mengacu pada mitologi pendirian brand: pertunjukan Spring/Summer 1993 karya Martin Margiela, di mana anonimitas adalah pernyataan tentang batin, bukan bukti akan pembungkaman.
Namun topeng versi Glenn Martens berbeda. Dan meski demikian, tampilannya begitu tulus. Dalam dunia couture, yang secara kodrat menolak arus komersial, terdapat ruang untuk bermain di batas-batas absurditas, dan dari situ, muncul sesuatu yang unik. Niat Glenn dalam menghadirkan referensi ini bukanlah untuk menjiplak, melainkan untuk menyatakan garis keturunan. Ini adalah topeng yang tulus, bukan untuk melindungi atau menyembunyikan, melainkan untuk mempertegas tatapan. Dalam hal ini, Glenn berhasil menghadirkan sesuatu yang dulu dikhawatirkan David Foster Wallace tidak mungkin ada: ketulusan yang mendalam, disampaikan melalui pastiche.

Dalam koleksi busana pria Fall 2025, seperti Jewel dari Wales Bonner dan debut yang sangat dinantikan dari Jonathan Anderson di Dior, referensi dihadirkan secara tulus, terkadang dipermanis dengan pin berhiaskan permata atau merujuk pada kode rumah mode era 1950-an. Ketulusan menjadi proses aktif yang ditampilkan di atas runway.
Di Prada, Raf Simons dan Miuccia Prada sejak lama menawarkan visi identitas yang dibentuk dari kontradiksi, di mana jahitan klasik disempurnakan oleh kancing yang tidak serasi, tekstur berlapis, dan siluet asimetris, semacam kekacauan elegan yang menyiratkan harmoni yang lahir dari kekacauan personal. Benang merah dari kerentanan emosional ini berlanjut ke pertunjukan busana pria mereka musim ini yang merangkul kelembutan dalam makna paling harfiah dan figuratif: rajutan tipis transparan, celana pendek bergaya kekanak-kanakan, dan luaran oversized yang lembut, membangkitkan citra softboy modern, bukan sebagai tren, melainkan sebagai arketipe emosional.
Ada ketulusan yang nyata dalam pendekatan mereka, dalam bagaimana struktur busana pria digunakan untuk membayangkan ulang kembali kontur maskulinitas itu sendiri.

Untuk menantang pandangan mendiang David Foster Wallace: bagaimana jika keberagaman bukanlah hukuman absolut? Bagaimana jika, setidaknya dalam konteks mode, justru merupakan sebuah anugerah?
Desainer seperti Glenn Martens, Jonathan Wes Anderson, Wales Bonner, Mrs. Prada, dan Raf Simons bukanlah pengikut seperti yang diperkirakan David Foster Wallace. Mereka bukan konsumen pasif dari klise-klise media massa. Atau setidaknya, bukan hanya itu; cara berpikir kolektif memang menjadi fondasi dari ekonomi tren yang membuat suatu hal dianggap in fashion. Tapi para desainer ini adalah pemikir yang tulus. Kini kita melihat bahasa visual dari referensi digunakan bukan untuk meratakan makna, melainkan untuk menumpuk dan memperkaya makna tersebut. Terkadang, justru busana yang paling artifisial, topeng, kacamata geek, atau sweter penuh gantungan hiasan, yang menyampaikan kebenaran emosional terdalam.
BACA JUGA:
Mengulik Tipe dan Nama Kain yang Mengisi Lemari Kita
Mengapa Para Selebritas Mendadak Ramai-Ramai Memakai Merchandise Lagi?
(Penulis: Maya Kotomori; Artikel ini disadur dari: BAZAAR US; Alih bahasa: Syiffa Pettasere; Foto: Courtesy of BAZAAR US)