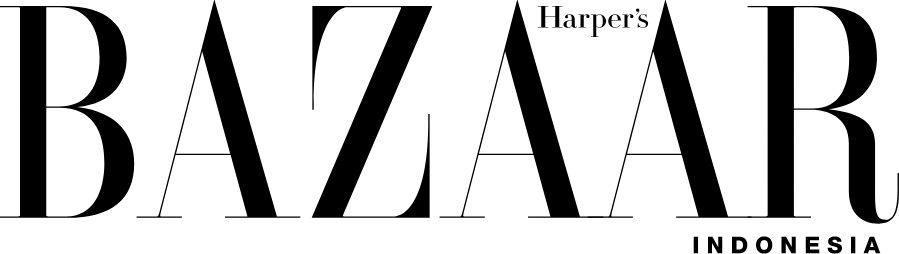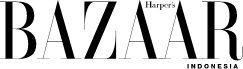Masyarakat kita terbiasa mengelompokkan dan fashion sejak pembuahannya dibingkai oleh pembagian antara womenswear dan menswear. Namun dengan identitas gender yang semakin fluid, tren-tren yang dikembangkan para desainer mencerminkan bahwa kejantanan juga begitu beragam: bahwa keperempuanan sangatlah bisa didekap oleh gender apa pun. Pada koleksi menswear tahun terakhir, khususnya, tren menswear feminin ini menjadi sorotan baru—dan ia akhirnya bermutasi menjadi golongannya sendiri.

Padahal, ini bukan hal baru: lihat saja busana panggung David Bowie, Elton John, atau Freddie Mercury pada tahun ’80-an; maraknya tren gender-neutral, unisex fashion yang dikembangkan Rad Hourani pada akhir 2000-an; hebohnya J.W. Anderson ketika ia mengeluarkan koleksi penuh dengan halter dan crop tops pada tahun 2014; suksesnya debut Alessandro Michele di Gucci, yang berhasil mengaburkan garis antara womenswear dan menswear sebagai ‘shared wardrobe’; dan toh, pria telah membeli womenswear sejak lama. Kanye West saja selalu memakai Céline pada era Phoebe Philo—dan pada saat itu, labelnya hanya memproduksi womenswear.
Baca juga: Mengenal Generasi Z: Mereka Si Generasi Segala Sarana Jenis Komunikasi

Namun, baru pada tahun 2021 ini kita berhasil mencapai titik ketika feminine menswear menjadi look yang dikenal secara umum. Andai saja perubahan dalam setengah abad terakhir bisa lebih cepat… bayangkan betapa beragamnya fashion jadinya! Akan tetapi, tampilan feminin sudah mulai diwakili oleh banyak sekali brand independen baru-baru ini, seperti Ludovic de Saint Sernin, Stefan Cooke, Palomo Spain, Harris Reed, Lazoschmidl, Alfin Varon, Ximon Lee, dan juga Nihl. Dengan konstruksi pas badan yang memperlihatkan bagian badan sensitif seperti pinggang, perut, punggung, dan bahkan pantat, desain mereka terlihat sangat sensual. Adapun label edgy yang terlihat lebih sporty, dan mengambil unsur-unsur club culture dan subkultur lainnya. Eckhaus Latta, Marine Serre, Telfar, Gmbh, Xander Zhou, Nicopanda, Pronounce, Acne Studios, Martine Rose, dan Charles Jeffrey Loverboy berhasil membuka sasaran tersebut pada pasar menswear.


Ada juga yang masih bergerak di ranah tailoring dengan gaya lebih arsitektural, seperti Daniel W. Fletcher, Carlota Barrera dan Botter, yang memberikan sentuhan feminin dengan bermacam-macam tekstur, detailing, dan material rapuh seperti mutiara, manik-manik kaca, dan crochet. Merek konglomerat seperti Jil Sander, dengan direksi Luke dan Lucie Meier yang sensitif, juga bermain pada area ini. Bahkan Alexander McQueen, di bawah pimpinan Sarah Burton, semakin konsisten membuat sebuah outfit dalam versi yang sama untuk womenswear dan menswear, hanya saja konstruksinya yang sedikit berbeda. Serupa, brand Random Identities oleh Stefano Pilati, mantan desainer Yves Saint Laurent, juga menawarkan style yang beririsan antara laki-laki dan perempuan. Lagi pula, banyak sekali pelanggan, apa pun gendernya, ingin bisa berbelanja tampilan yang sama dengan konstruksi dan ukuran yang tepat untuk badannya.


Perkembangan ini tidak hanya terlihat di ranah mode—ia melampaui runway ke panggung utama. Bulan April kemarin, Kid Cudi membawakan lagu Sad People di panggung Saturday Night Live dengan mengenakan gaun Off-White custom sebagai penghormatan kepada mendiang Kurt Cobain. Desain floral rancangan Virgil Abloh tersebut terinspirasi oleh look yang dikenakan penyanyi, penulis, dan gitaris Nirvana pada sampul majalah The Face pada tahun 1993, meskipun motifnya diambil dari dress yang dipakainya pada tahun 1989. Sayangnya, kedua pria cisgender (orang yang mengidentifikasi dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya) tidak mengungkit konteks sosial apa pun. Padahal, dengan platform mereka, bisa sangat berguna, khususnya untuk komunitas LGBTQ+ yang sering kali dalam situasi terancam, hanya karena cara mereka berpakaian. Kurt sendiri memilih busananya karena alasan kenyamanan, “[Memakai dress] mungkin subversif untuk orang yang belum pernah melihat pria berpakaian sebelumnya atau yang tidak nyaman dengan konsep tersebut, tapi saya tidak peduli tentang orang-orang tersebut. [Memakai dress] itu tidak subversif.” Ia juga mengatakan, “Memakai dress menunjukan bahwa saya bisa sefeminin yang saya inginkan. Saya heteroseksual, tetapi jika saya homoseksual, itu pun tidak masalah.” Tentu. Dia Kurt Cobain.

Sebelumnya, Harry Styles juga menjadi perbincangan hangat karena tiga setelan outfit Grammys-nya yang dipadukan dengan feather boa. Ia sempat juga dituduh queerbaiting, di mana seseorang sengaja menyiratkan karakteristik queer, hanya sebagai umpan marketing, tanpa memiliki representasi sepenuhnya. Harry, yang tidak pernah menyatakan seksualitasnya secara jelas, sempat menjelaskan tanggapannya soal pakaian dan gender. “Ketika Anda menghapus mentalitas ‘ada pakaian untuk laki-laki, dan ada pakaian untuk perempuan,’ Anda menghapus arena tempat Anda bisa bermain.” Ia bukan satu-satunya yang berpakaian demikian: Billy Porter juga sering kali mengenakan gaun pada red carpet. Pada media sosial, orang heteroseksual biasa seperti @markbryan911 menjadi viral belakangan ini karena gayanya yang memadukan rok dan stiletto dengan tailoring. “Saat orang melihat foto saya, mereka langsung berasumsi saya gay,” jelasnya. “Namun yang terus memotivasi saya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa saya membantu mereka melihat hal dalam cara yang selalu mereka inginkan, tapi dengan ketakutan, sebelumnya.”
Biasanya, dalang dari ketakutan ini adalah misogini, yang telah berdampak kepada semua gender sepanjang sejarah dan melahirkan toxic, hyper-masculinity. Nilai-nilai seperti keseriusan, kekuasaan, dan kredibilitas dilekatkan kepada maskulinitas, sedangkan feminitas dibuat antitesis, sehingga kesetaraan tidak bisa dicapai perempuan.
Tulisan John Berger di Ways of Seeing sangatlah akurat mendeskripsikan ini, “Anda melukis seorang wanita telanjang karena Anda senang melihatnya, Anda meletakkan cermin di tangannya dan Anda menyebut lukisan itu “kesombongan”, dengan demikian secara moral mengutuk wanita yang ketelanjangannya Anda gambarkan untuk kesenangan Anda sendiri.” Sebelum akhir periode Rococo di Prancis pada abad ke-18, pakaian pria lebih mewah, rumit dan feminin daripada baju perempuan. Formal suit para bangsawan pada waktu itu, habit à la française, yang terdiri dari coat, waistcoat dan breeches (celana pendek) sering kali disulam dengan benang warna emas atau perak, memiliki detail ornamental seperti ruffles dan renda, dan dibuat dari kain berwarna pastel, bermotif bunga yang rumit, atau garis-garis tebal. Ada masanya dalam sejarah ketika tidak ada rasa malu yang terlekat dengan feminitas.
Dan sekarang, perhatikan saja bagaimana womenswear dibentuk—‘kekuatan’ yang dimilikinya dipinjam dari menswear: utilitarianism berasal dari pakaian militer; tren power shoulders untuk wanita karier tahun ‘70-, ’80-an terjadi untuk melawan lingkungan kerja yang didominasi pria; kebanyakan pelopor minimalism pada womenswear sebelum tahun ’90-an merupakan desainer laki-laki; bahkan narasi revolusi perempuan pada tahun ’20-an selalu disimbolisasikan oleh Coco Chanel yang ‘menyediakan’ celana. Kalaupun ini hanya penyesuaian untuk tujuan yang lebih besar, narasi yang tertulis memberikan ilusi bahwa maskulinitas lebih bernilai daripada feminitas, padahal tidak seharusnya demikian. Seakan-akan perempuan tidak memiliki pilihan dan harus beradaptasi dengan laki-laki, seakan-akan derajat kita lebih rendah, dan harus diangkat… dengan berpakaian seperti mereka.

Feminitas, untuk gender apa pun, adalah sesuatu yang harus selalu dikultivasi dan dikembangkan, terutama karena masyarakat kita menganggap keperempuanan begitu mengancam. Sekarang, ini merupakan simbol kekuatan, pembangkangan, pemberontakan—dengan itu, melawan ekspektasi bahwa kita harus berpakaian sesuai pembagian gender dan juga melawan gender power relations. Maskulinitas telah berubah dan akan terus berevolusi menjadi sesuatu yang tidak mencengkeram—itu patut dirayakan oleh siapa pun, tanpa ketakutan atau penyesalan.
Baca juga: 6 Tren Fashion Fall/Winter 2021 Pilihan Editor Bazaar untuk Anda Coba
(Penulis: Allysha Nila, Layout by : Sophie El Fasya, Foto: Courtesy of Alexander McQueen, Botter, GmbH, Ludovic de Saint Sernin, Martine Rose, Palomo Spain, Harris Reed, Daniel W Fletcher, Carlota Barrera)