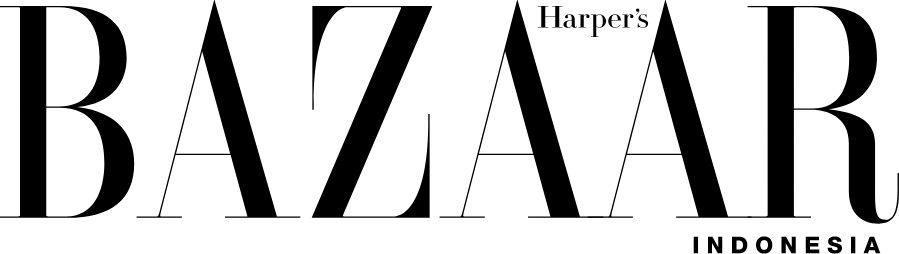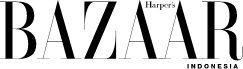Suatu sore musim gugur lalu di Roma, saya berjalan di sepanjang sungai ketika seorang wanita muncul dari tikungan dengan penampilan yang membuat saya terkejut. Ia mengenakan visor hitam terbalik di kepalanya seperti mahkota—membuatnya tampak seperti paus Goth—dipadukan dengan atasan hitam, celana lebar terbelah di sisi, serta tas jinjing hitam Pleats Please Issey Miyake. Bibirnya berwarna ungu tua bak anggur Nebbiolo, sementara matanya tersembunyi di balik kacamata perak kecil yang mengingatkan pada shutter shades yang sempat populer di era 2000-an, tetapi dengan sentuhan yang lebih artistik.
BACA JUGA: Simak 50 Tampilan Para Pesohor Glamor Hollywood Menyambut Hari Natal Pada Zamannya
Saya begitu terpesona hingga berhenti, berbalik, dan mulai mengikutinya. Tidak terlalu dekat—saya tidak ingin dianggap menyeramkan—tetapi ada sesuatu yang membuat saya terpikat, bukan hanya pada cara ia berpakaian, tetapi juga pada cara ia membawa dirinya. Ia berjalan perlahan, dengan langkah santai penuh percaya diri seperti Elvis, bahunya bergerak mengikuti ritme langkahnya. Dari belakang, saya bisa melihat rambut peraknya dikuncir ketat dan dijepit dengan peniti berbentuk martini—pemandangan paling glamor yang pernah saya lihat dalam waktu yang lama.
Glamor kini semakin langka. Seiring dengan semakin longgarnya aturan berpakaian dan mode yang semakin massal, kapan terakhir kali Anda melihat seseorang yang benar-benar memancarkan glamor? Yang membuat Anda terpana? Di era algoritma, produk dupe dari Amazon, “wajah Instagram,” dan “wajah Ozempic,” semakin mudah dan dapat diterima untuk tampil seragam. Itulah sebabnya ketika seseorang benar-benar berusaha dalam berpenampilan, mereka langsung mencuri perhatian.

“Glamor itu butuh waktu,” kata penata gaya selebriti Kate Young. Dengan banyaknya aktor yang berusaha keras meniru gaya Hollywood klasik di musim penghargaan ini, saya pikir ia bisa memberi wawasan tentang fenomena tersebut. Contohnya, Ariana Grande yang begitu total meniru Audrey Hepburn di Golden Globes dengan mengenakan gaun rancangan Hubert de Givenchy dari tahun 1966, hingga media berspekulasi apakah ia tengah mengincar peran dalam film biopik Audrey. Tetapi glamor bukan sekadar kostum yang bisa dikenakan; ini adalah cara seseorang bergerak di dunia.
“Jika Anda menata rambut dengan rol, itu memakan lebih banyak waktu dibanding sekadar membuat beach wave, dan pengalaman itulah yang membentuk glamor,” jelas Kate. “Mengenakan gaun dengan banyak kait dan interior belts, daripada sekadar slip dress atau sheath dress tanpa zipper, mengubah proses berpakaian menjadi sebuah ritual. Ritual inilah yang kita perhatikan ketika melihat seseorang di jalan—seperti para wanita tua di Madison Avenue yang mencocokkan tas, sepatu, dan lipstik mereka. Ini bukan sekadar konsumsi, tetapi penghormatan terhadap waktu dan perhatian terhadap detail, sesuatu yang dapat diapresiasi baik oleh yang mengenakan maupun yang menyaksikan. Itu yang membuat kita berhenti dan berpikir, ‘Wow, keren.’”
Sering kali, kita mengasosiasikan glamor dengan masa lalu—khususnya dengan wanita-wanita yang gaya berpakaiannya terbentuk sebelum internet mengubah segalanya. Pengabdian terhadap penampilan terasa lebih autentik ketika tidak dilakukan demi jumlah like atau engagement. Karena kini “selera yang baik” bisa dengan mudah didefinisikan dan diakses—cukup dengan membeli sabun tangan “yang tepat,” sandal “yang tepat” dari Paris, sofa vintage “yang tepat” dari Italia, mantel “quiet luxury” yang tepat, dan voilà!—maka muncullah nostalgia akan masa ketika segala sesuatu terasa lebih istimewa dan unik. Kita merindukan sesuatu yang tidak bisa diduplikasi.


Claibourne Poindexter, spesialis perhiasan senior dan wakil presiden di Christie’s, mengatakan bahwa dalam lelang Magnificent Jewels Desember lalu, terdapat minat yang luar biasa tinggi dari pembeli muda terhadap barang-barang yang memiliki sejarah—seperti gelang berlian milik mantan editor mode Harper’s Bazaar Diana Vreeland, atau koleksi pribadi desainer interior dan filantropis Mica Ertegun, istri dari salah satu pendiri Atlantic Records, Ahmet Ertegun. “Orang-orang berlomba mendapatkan barang yang mencerminkan kepribadian mereka,” katanya. “Mereka ingin sesuatu yang tidak akan dikenakan orang lain di ruangan yang sama.”
Jika selera dapat dipelajari, baik oleh manusia maupun algoritma, maka glamor adalah rahasia yang dijaga ketat. Siapa pun bisa mengaksesnya—tetapi tidak tanpa usaha, dan justru itulah intinya. Anda tidak perlu membeli perhiasan atau gaun seorang tokoh ikonis untuk menjadi glamor, begitu pula tidak perlu meniru mob wife aesthetic atau gaya Hollywood klasik. Justru sebaliknya.
Glamor adalah sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Ini bukan tentang memiliki barang “yang tepat,” melainkan bagaimana seseorang membawa dirinya.
Berakar dari unsur magis dan intelektualitas, kata glamor diyakini berasal dari bahasa Latin untuk "grammar," yang dalam abad ke-18 merujuk pada studi akademis, termasuk praktik okultisme. Glamor adalah kekuatan tersembunyi—sesuatu yang dapat dikendalikan, layaknya mantra yang memesona.
Dalam Glamour: A History (2008), Stephen Gundle mendefinisikannya sebagai “kemampuan mengubah seseorang yang biasa menjadi sosok impian.” Pada akhir 1930-an, maknanya beralih dari kesan mistis menjadi lebih kapitalistik, terkait dengan Hollywood dan dunia mode. Sosok seperti Josephine Baker, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, dan Marilyn Monroe tampak melampaui realitas sehari-hari. Namun, daya tarik mereka bukan sekadar hasil dari uang, ketenaran, atau kekuasaan, melainkan dari pengalaman, wawasan, serta penciptaan kode gaya yang unik melalui eksplorasi dan keingintahuan tanpa henti. Tak semua bintang itu glamor, dan tak semua orang glamor adalah bintang.
Jalil Johnson, seorang penulis dan kreator digital yang mengadaptasi gaya ala Jackie Kennedy, menganggap langganan Criterion sebagai hal paling glamor yang ia lakukan di tahun 2024. Dalam buletinnya, Consider Yourself Cultured, ia mengajak pembacanya untuk menjalani hidup yang kaya akan budaya—bukan hanya dalam fashion, tetapi juga film, buku, dan pengalaman. “Sepanjang 2024, banyak yang membahas ‘bagaimana menjadi berkelas,’” ujarnya. “Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai begitu saja. Itu soal hidup, belajar, membaca, dan menonton Sunset Boulevard. Harus dijalani.”
Saat berbincang dengan Jalil, ia mengaku lelah dengan tren quiet luxury—di mana orang terus-menerus diberitahu tentang barang mewah tertentu yang “tepat” untuk menunjukkan kelas mereka. “Kalau mengikuti estetika itu, lama-lama tidak ada tujuannya,” katanya. “Setelah punya sweater atau mantel itu, lalu apa?” Sebuah mantel desainer mungkin memproyeksikan citra hidup yang mapan, tetapi tidak memiliki kisah yang nyata di baliknya. Berbeda dengan glamor, quiet luxury bisa dengan mudah ditiru.
“Dengan quiet luxury, orang cenderung membeli produk yang sama,” ujar penata gaya Anny Choi, yang lebih tertarik pada koleksi vintage serta desainer independen seperti Attersee dan Colleen Allen. “Aku tidak ingin tas yang dimiliki semua orang; aku ingin sesuatu yang memicu percakapan.”
Tahun lalu, Choi mengunjungi One/Of, sebuah atelier made-to-measure di Upper East Side, untuk memesan rok maxi custom terinspirasi oleh Carolyn Bessette Kennedy. Patricia Voto, pendiri One/Of, menjelaskan bahwa kliennya menginginkan sesuatu yang unik—saat datang ke pesta atau jamuan makan siang, mereka ingin menjadi satu-satunya yang mengenakan busana tersebut. Proses membuat janji dan berkonsultasi secara eksklusif pun menjadi bagian dari pesonanya.

Membangun cerita adalah inti dari glamor. Pada 1936, Diana Vreeland, editor fashion legendaris majalah ini, memulai kolom ikonisnya dengan pertanyaan sederhana: Why Don’t You?—mengajak pembaca untuk “mengancingkan diri ke dalam gaun malam” atau “memakai sarung tangan beludru yang mencolok” atau “mengubah mantel bulu tua menjadi jubah mandi.” Glamor adalah tentang menciptakan narasi, bahkan jika hanya untuk diri sendiri.
“Saya menyukai usaha di balik glamor,” ujar Dara, seorang penata gaya yang terkenal dengan caranya berpakaian yang all-out tanpa terkesan berlebihan, dalam podcast majalah ini, The Good Buy. “Bagi saya, glamor adalah mekanisme bertahan hidup. Cara saya memahami dan memproses dunia. Saya memandang fashion sebagai kata kerja: to fashion. Anda membentuk diri sendiri. Anda menciptakan sesuatu dari apa yang ada di sekitarmu dan menggunakannya untuk membangun cerita dari perasaan Anda."
Namun, glamor tidak selalu memerlukan waktu berjam-jam untuk berdandan. Wes Gordon, direktur kreatif Carolina Herrera yang mendesain gaun spektakuler untuk gala, percaya bahwa glamor lebih dari sekadar pakaian: “Itu tentang membeli bunga untuk diri sendiri. Tentang buku yang kamu baca, teman yang menemani makan malam.” Bukan apa yang dipakai, tetapi cara seseorang mengenakan sesuatu. Baginya, glamor adalah “menempatkan keindahan di posisi tertinggi.” Mencarinya, merayakannya—tetapi dengan tanda seru—membuatnya menjadi sesuatu yang memesona dan menggoda.


Di tengah banyaknya keburukan dunia, melakukan sesuatu yang kecil bisa menjadi cara melawan kegelapan, kata Wes. Bukan berarti glamor bersifat moral atau altruistik. Justru, ia tidak alami dan tidak biasa. Itu bisa berupa sarapan mewah atau berjalan kaki tanpa tujuan. Sebuah bentuk penolakan terhadap kebosanan hidup dan status quo. Kadang berlebihan, bahkan sedikit norak. Seperti yang ditulis Gundle, glamor adalah kombinasi kontradiktif dari “elegansi yang cabul, eksklusivitas yang mudah diakses, dan elitis yang demokratis.”
Ketika memikirkan sosok glamor di masa kini, yang muncul bukan mereka yang mengenakan sarung tangan opera, topi besar, atau mantel bulu panjang—kode itu hanya meniru sesuatu yang sudah pernah ada. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kenikmatan dibanding kepemilikan. Kritikus fashion The Washington Post, Rachel Tashjian, pernah mengkritik tampilan konservatif dalam pelantikan era Donald Trump, membandingkannya dengan kemewahan kaku Nancy Reagan. “Tidak ada unsur fantasi,” katanya. “Mereka hanya menaruh fesyen dalam kebosanan masa lalu.” Gaun Givenchy Ivanka Trump, misalnya, hampir meniru persis gaun Audrey Hepburn di Sabrina.
Bagi saya, glamor modern ada pada sosok Chappell Roan dan Doechii, Dara dan Jalil Johnson, atau perempuan di Roma yang asyik dengan dunianya sendiri—orang-orang yang menikmati berpakaian, bepergian, makan, minum, dan berbagi kebahagiaan dengan dunia. glamor bukan soal status, melainkan kemurahan hati dalam berbagi kesenangan. Saat seseorang menikmati hidup, ia memancarkan daya tarik yang selaras dengan definisi glamor yang asli. Kita ingin menjadi mereka, ingin berada di sekitar mereka.
Glamor modern tidak selalu rapi; ia bisa berantakan. Ia tidak pernah puas. Seperti karakter Nicole Kidman dalam Babygirl, ia menginginkan lebih. Dan ia tidak malu mengatakannya. Kenapa tidak menari dengan penuh kesungguhan diiringi Father Figure dari George Michael sambil memakai bathrobe? Kenapa tidak memesan segelas susu dingin? Kenapa tidak mengatakan dengan jujur apa yang benar-benar membuatmu bergairah? Menikmati sesuatu kadang bisa terasa memalukan, tapi seharusnya tidak perlu begitu. Kenapa tidak meraihnya dan menikmatinya?
BACA JUGA:
Tampil Glamor dengan Setelan Power Suit bersama Tatjana Saphira
Zendaya Memberikan Tips Bergaya di Atas Karpet Merah dari Tampilan Color Blocking
(Penulis: Emilia Petrarca; Artikel ini disadur dari BAZAAR US; Alih bahasa: Aleyda Hakim; Foto: Courtesy of BAZAAR US)
- Tag:
- glamor