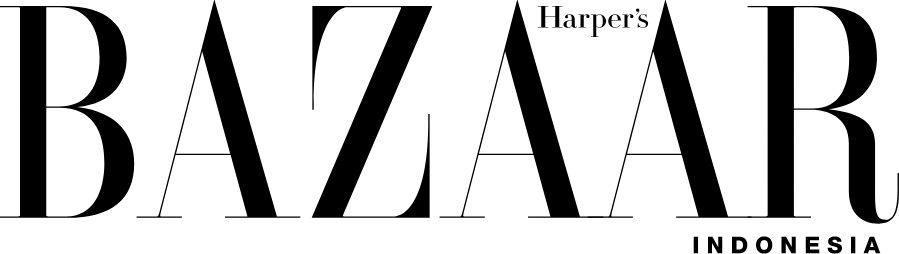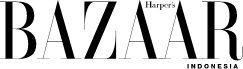Beberapa waktu lalu, Bazaar menghabiskan hari dengan sejarah Indonesia. Topik perbincangan dengan kakak beradik, Jay dan Chitra Subyakto, pun mengingatkan setiap generasi penerus bahwa inspirasi bisa datang dari negeri sendiri, jangan lupa berbagi, dan dunia politik itu tidak selalu negatif. Merekalah saksi hidupnya. Simak percakapannya di bawah ini.
Harper’s Bazaar (HB): Dibesarkan di kontinen yang berbeda, apa yang sering kalian bicarakan saat membahas Indonesia?
Chitra Subyakto (CS): Karena saya seorang adik, pasti saya paling banyak belajar. Kita ngobrol apa ya, mas?
Jay Subyakto (JS): Jadi begini, sampai umur enam tahun saya tinggal di Turki dan Yugoslavia. Di sana, saya bersama kakak-kakak lebih banyak diberi tahu tentang Indonesia. Sebaliknya dengan Chitra, karena dari lahir dia sudah di Jakarta, dia tidak perlu dikasih tau banyak tentang Indonesia. Zaman dulu, orang tua itu takut kalau anaknya tidak cinta dan tidak kenal dengan Indonesia. Jadi, ayah selalu bilang kalau kita adalah duta bangsa indonesia. Saat di luar negeri jangan terus berbusana seperti orang luar, tapi justru harus Indonesia.
CS: Benar, ibu itu selalu bikin kebayanya sendiri.
JS: Iya.
CS: Semuanya sendiri. Tidak pernah ke salon, ke penjahit pun tidak pernah.
JS: Semua serba sendiri. Salah satu ajaran ayah terhadap saya untuk menjadi duta bangsa ini adalah waktu saya dibawa ke tempat-tempat yang ada racist-nya. Di situ ayah saya bilang bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya rasialisme, semuanya gotong royong. Jadi diberi contoh kalau di sana itu sangat individualis, di Indonesia justru kebalikannya. Itu yang ditanamkan ke saya.
CS: Contoh yang paling dekat ke saya adalah ajaran ibu tentang kain. Dari koleksinya ibu bercerita tentang sejarah kain, tanpa saya sadari itu sangat menempel. Jadinya, kalau bepergian saya selalu mencari kainnya. Dari kain, kita bisa tahu budaya di situ seperti apa, udaranya bagaimana. Intinya, mereka mengajarkan kita harus melihat sesuatu lebih dalam, tidak hanya luarnya saja.
JS: Kita memang diajarkan kalau keindonesiaan itu jangan dekoratif. Sewaktu ibu masih menjadi ibu Duta Besar, kalau diundang ke pesta, ibu tidak berbusana menggunakan ball gown, dia tetap memakai kain. Jadi, dia kasih tau ke Chitra bagaimana cara mengombinasikan kain dengan fur, dan jadinya tidak sok Barat. Fungsional tapi tetap Indonesia. Sama dengan perhiasan, ibu mengoleksi cincin dan kalung Majapahit. Dia tidak beli Van Cleef & Arpels, ya. Sewaktu mereka masih hidup, kita sering pergi berlibur ke Yogyakarta, Bali, atau ke daerah lainnya. Dibawa ke candi, ke gunung, ke toko antik, bukan tempat yang terlalu turis. Pokoknya ke tempat yang anak kecil kurang suka!
CS: Saya ingat sekali kalau hari Minggu, pasti dibawa ke toko buku! Terus selalu tanya, “Kita boleh beli berapa kalau beli buku?” Jawabannya selalu terserah. Kalau mainan, tidak boleh.
JS: Kalau sekarang, kita berkumpul sering karena kerjaan, ya?
CS: Iya!
JS: Saya juga banyak kerjanya sama Chitra. Tapi saya sangat berhutang budi dengan kakak saya, Sita. Dia yang pertama kali mengajak saya untuk foto secara komersil. Dengan Chitra karena saya banyak bikin pertunjukkan musik. Tapi saya tidak mau dibilang KKN! Bukan! Dia punya prestasi di mana-mana baru saya rangkul. Dulu kita pernah sepakat kalau tahun baru harus pergi sama-sama. Topik yang dibicarakan pasti bagaimana kita merindukan orang tua, lalu bicara tentang keadaan bangsa, politiknya, dan juga manusianya. Untungnya saya, Chitra, Sita, dan yang lain itu selalu punya pekerjaan yang berhubungan dengan seni. Kita selalu mencoba menampilkan keindonesiaan kita zaman sekarang. Kreativitas kan juga harus dikembangkan.
CS: Sesuai zamannya, ya.
JS: Iya, dan selama ini kita sudah di jalur yang benar.
Zaman dulu, orang tua itu takut kalau anaknya tidak cinta dan tidak kenal dengan Indonesia.
- Jay Subyakto
HB: Berhubungan dengan Tanah Air, Bazaar ingin tahu bagaimana Pancasila diaplikasikan dalam keluarga Subyakto?
JS: Untungnya kita punya paman Mohammad Hatta. Ibu saya adalah adik dari ibu Rahmi Hatta. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu jemput ibu di rumah Bung Hatta. Nah, kala itu Bung Hatta bercerita bagaimana dia dan Bung Karno menemukan Pancasila. Yang bukan main adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelihatan sekali bahwa dua founding fathers ini sangat menjunjung tinggi frasa Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman yang harus dipelihara, toleransi, dan agama. Untung sekali buat saya bisa melihat sosok Bung Hatta, ya. Seorang politikus yang benar-benar berjuang untung bangsa dan negaranya, tidak korupsi, jujur, kemudian mau mengundurkan diri kalau tidak sejalan. Jarang sekarang kita lihat tokoh-tokoh politik yang pemikirannya bukan main seperti Bung Hatta ini.
CS: Karena saya waktu itu masih kecil, saya sering dibawa sama ibu untuk main ke situ. Kita manggilnya om Hatta, ya.
JS: Iya. Om Hatta.
CS: Jadi om Hatta selalu suruh saya pilih buku. Dia selalu cerita, buku itu penting sekali. Bung Hatta pernah berucap “Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” Saya setuju, karena dengan membaca, imajinasi kita bisa kemana-mana. Itu yang saya ingat sekali sejak kecil.
HB: Apa makna kata sejahtera dalam keluarga?
JS: Kalau sejahtera itu sebenarnya cukup. Susah sekali dalam hidup untuk mengatakan kita sudah cukup. Sejahtera itu juga harus punya empati ke orang lain, sehingga jangan kita saja yang sejahtera dan makmur. Kalau semua bisa menikmati apa yang ada di bumi ini. Seperti kata Mahatma Gandhi, Bumi ini cukup untuk seluruh manusia di dunia, tapi tidak cukup untuk kerakusan manusia.
CS: Idem!
HB: Menurut kalian, kenapa budaya Barat selalu dianggap unggul?
JS: Selama 350 tahun kita dijajah oleh bangsa yang besarnya hanya sebesar Jawa Timur. Itu yang buat kita jadi rendah hati dan selalu menganggap bahwa kaum Barat itu lebih unggul. Kita tidak pernah mengangkat literasi atau kebudayaan vernakular di Indonesia. Padahal ada. Justru kita hancur saat mengadopsi budaya Barat. Lihat saja plastik, iya kan? Kita tidak pernah lagi melihat Genius Loci atau kearifan lokal yang dipunyai oleh nenek moyang kita. Padahal kalau dibaca di Serat Centhini dan Babad Tanah Jawi, filosofi konsep hidup kita itu begitu tinggi. Maka saya selalu ingin orang untuk tahu bahwa ada masanya Indonesia punya agama nusantara yang tidak pernah ada konflik SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan). Kita sangat permisif dan selalu menerima budaya luar tanpa melihat potensi kita sendiri.
CS: Simpelnya, rumput tetangga terlihat lebih hijau.
JS: Nah, betul seperti itu.
CS: Padahal rumput tetangganya palsu, itu dari plastik! Iya kan!
Sesuatu yang diakui di luar negeri itu akan menjadi trigger untuk bangsa ini bangkit.
- Chitra Subyakto

JS: Begini, sebenarnya kita ini adalah bangsa yang tidak punya musuh. Kita bisa maju kalau kita punya tujuan. Lihat Singapura dan Amerika dengan moto negaranya sendiri. Kita tidak punya! Akhirnya kita ribut dengan diri sendiri. Bangsa ini tidak punya rencana ke depan, tidak punya motivasi. Kalau punya musuh, kita pasti bersatu. Seperti di pertandingan bola, begitu kita melawan Malaysia, kita punya motivasi tinggi dan jadi satu. Itu sih yang perlu. Harus punya motivasi, tujuan, dan dendam yang positif.
CS: Jadi seharusnya agama Indonesia itu bola, ya?
JS: Iya. Kalau Inggris kan bilang seperti itu, agama mereka itu adalah bola.
HB: Lalu bagaimana cara generasi penerus menerapkan nilai nasionalis dalam diri?
JS: Nasionalisme itu harus dari orang tua. Sekolah internasional zaman sekarang itu sedikit sekali mempelajari tentang sejarah ataupun kebudayaan Indonesia. Nasionalisme itu sebenarnya dipupuk oleh orang tua, dan parahnya semua media itu sangat mengagungkan budaya luar. Banyak yang berkarya tapi referensi selalu dari luar, yang artinya sudah pernah dibuat. Padahal nenek moyang kita menciptakan apa pun tanpa referensi dari luar, hanya menggunakan rasa dan kebiasaan sendiri.
CS: Bangun Candi Borobudur tidak pakai referensi.
JS: Iya. Kita lihat arsitekstur Indonesia, kulinernya, literasinya, karya sastranya itu tidak ada di luar negeri.
CS: Contoh menarik lainnya adalah batik. Begitu suatu hari negara tetangga mengakui bahwa batik milik mereka, baru orang Indonesia ribut. Sempat saya ditanya pendapat tentang hal itu. Saya jawab “Tidak apa-apa! Justru kalau mereka tidak mengakui, orang kita juga cuek aja.”
JS: Iya, pasti.
CS: Sesuatu yang diakui di luar negeri itu akan menjadi pemicu untuk bangsa ini bangkit. Kayak waktu itu, mas pernah bikin pertunjukan Matah Ati, justru mas inginnya di luar negeri dulu. Karena kalo berbau luar negeri, justru orang baru mau nonton.
JS: Iya.
CS: Baru sesudah itu di sini.
JS: Memang ironisnya dulu waktu Matah Ati mau dibuat pertama kali di Indonesia, saya bilang jangan, karena pasti tidak laku.
CS: Karena orang akan menganggap itu adalah sekadar tarian Jawa.
JS: Jadi harus main di luar negeri dan di tempat yang representatif, bukan di kedutaan. Ternyata strategi itu tepat. Ketika kita diapresiasi di luar negeri baru akhirnya kita diapresiasi oleh bangsa sendiri. Bangsa kita itu reaktif. Kalau orang lain heboh, baru kita mau melihat bahwa ternyata Indonesia punya warisan yang bukan main. Itu yang harus kita jaga, jangan lagi kita gampang dipengaruhi oleh budaya asing, dan jangan pernah meremehkan bangsa sendiri.
CS: Sama sepertinya bangsa kita itu pelupa dan mudah memaafkan. Sebenarnya itu hal yang bagus, tapi juga cepat lupa sejarah.
JS: Itu dia sayangnya. Generasi sekarang itu kiblatnya selalu ke Barat. Selalu ikut-ikut. Padahal menurut saya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan selain mengikuti apa yang dilakukan di Barat sana. Balik lagi, kesalahnya ada di pendidikan. Kita selalu menjadi bangsa yang minder atau rendah diri karena tidak pernah ada prestasi yang dibanggakan. Padahal banyak anak muda kita yang hebat, juara matematika, sadar lingkungan. Tapi tidak pernah dapat panggung yang tepat, justru yang dapat malahan orang-orang yang tidak berguna.
CS: Sistem pendidikan kita juga bikin kita takut tunjuk tangan, di kelas. Zaman dulu kan semuanya harus seragam, harus iya.
JS: Sama dalam pendidikan, kita itu menjadikan seni nomor tiga. Padahal salah satu aspek dari budaya itu kan seni. Itu yang tidak pernah ada di sekolah. Sehingga akhirnya hanya menjadi kumpulan dari yang mereka tiru. Yang saya syukuri dengan pandemi ini kita bisa lihat hitam putihnya orang. Kelihatan kedewasaan sebuah negara. Ada yang apatis, mempunyai empati tinggi, ada yang tidak perduli. Tingkat intelektualitas setiap negara juga kelihatan. Sebenarnya ini peringatan dari alam, untuk tidak rakus. Cobalah untuk berbagi semesta ini.
CS: Pandemi ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan semua orang untuk berubah. Semua orang bisa berusaha, berbisnis, berpolitik atau apa pun itu dengan lebih ramah lingkungan.
JS: Benar.
CS: Di masa seperti ini kita bisa lihat siapa yang peduli dan punya hati.
Susah sekali dalam hidup untuk mengatakan kita sudah cukup.
- Jay Subyakto

HB: Sekarang karier, kenapa berujung di seni?
JS: Karena dulu saya kuliah arsitektur, tapi pas lulus, ternyata tidak laku jadi arsitek. Jadi akhirnya cari pekerjaan yang lain. Sebenarnya saya dari dulu lebih senang ke dunia sinematografi, hanya tidak diizinkan oleh orang tua. Harus jadi insinyur, akhirnya saya pilih arsitektur. Saya tahu bahwa arsitektur ini sebenarnya adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan dan akar pemikiran. Sehingga khayalan saya bisa saya buat sendiri, bukan hanya menghayal. Makanya saya tidak setuju kalau seni itu jadi sesuatu yang tersier atau yang kesekian, karena seni itu inti dari semua penciptaan dan pemikiran.
CS: Karena saya paling bungsu, saya punya contoh empat orang kakak. Jadi dari saya umur tujuh tahun, saya sudah belajar les tari dari ibu Retno Maruti. Nah, waktu SMA, saya dipanggil ayah dan diminta berhenti, “Ini kakak kamu, empat orang, semuanya menuju jadi seniman. Seniman itu tidak ada duitnya. Kamu harus ambil Fisika dan Ekonomi. Lalu kamu kerja di bank, supaya bisa urusin uang kakak-kakak kamu.”
JS: Padahal tidak ada uangnya juga!
CS: Karena ayah bilang seniman itu tidak bisa menghitung duit, mas! Jadi akhirnya saya berhenti dan mengikuti kemauan beliau. Selesai kok, meski dengan hati yang berat. Sesudah itu saya bilang ke ayah bahwa saya tidak mungkin kerja di bank karena tidak suka. Dari kecil ayah dan ibu sudah mengajak kita melihat candi, wayang orang, dan lainnya. Sebenarnya sudah tertanam seni dari kecilnya.
JS: Sebenarnya mereka yang salah, sih.
CS: Iya, mereka yang salah! Akhirnya saya masuk ke dunia fashion di tahun 2000. Lalu saya itu sama seperti mas Jay, bosanan. Jadi pindah ke film, musik, dan macam-macam. Sampai akhirnya membuat Sejauh Mata Memandang. Benang merahnya adalah kain.