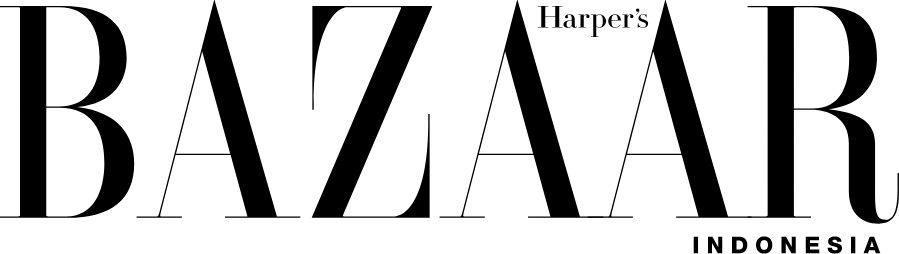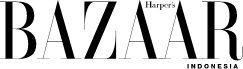Jakarta tak perlu ode, sebab ia senantiasa masyhur meski jejaknya tak lagi sama.
Jakarta tak perlu ode, ia perlu kenangan masa lalu agar jiwanya senantiasa terjaga.
Maka tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk memahami sejarah, agar jati diri bangsa terus abadi. Begitu pula dengan sejarah kota Jakarta. Sejatinya, mengenal Jakarta bukan hanya akan menelusuri jejak sejarah kemerdekaan bangsa ini, lebih dari itu, Jakarta adalah kisah tentang selebrasi keragaman yang nyata.
Mungkin tiada yang menyangka jika ibu kota yang merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara berbekal luas sekitar 661,52 kilometer persegi ini dahulunya hanya bermula di Kali Ciliwung.
Tepatnya sejak lebih dari 500 tahun silam, Jakarta adalah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung seperti disebutkan Willard A. Hanna dalam bukunya bertajuk Hikayat Jakarta, “Dahulu, Sunda Kelapa terbujur sepanjang satu atau dua kilometer di atas potongan-potongan tanah sempit yang dibersihkan di kedua belah pinggir Sungai Ciliwung yang sempit, dekat muaranya, dekat sebuah teluk yang terlindung oleh beberapa buah pulau.”
Lantas bandar ini bertumbuh kembang menjadi salah satu pusat perekonomian di daerah Jawa, bahkan menjadi bandar terbesar di daerah Sunda.
 1.jpg)
Menurut Willard, “(Sunda Kelapa) sudah dikenal selama 75 tahun oleh para saudagar perintis bangsa Portugis di wilayah Pasifik, Sunda Kelapa mulai menarik perhatian orang Eropa lain melalui Jan Huygen Van Linschoten, seorang pelaut Belanda yang menemukan rahasia-rahasia perdagangan dan navigasi bangsa Portugis.”
Melalui buku yang ditulis Willard itu, turut terungkap bahwa bukan bangsa Portugis yang menjadi pedagang asing pertama dalam mencari bandar lada Pulau Jawa. Dahulu Sunda Kelapa adalah bagian dari kerajaan Sunda yang pernah sangat berjaya, dan memiliki ibukota yang berada dekat dengan daerah Bogor.
Seperti yang sudah dapat Anda tebak, sebagai pusat perdagangan di Asia, tentu saja di Sunda Kelapa terjadi interaksi-interaksi antar etnis dan ras. Berabad-abad sebelum kemunculan bangsa Eropa di Nusantara, telah hadir saudagar asal Arab dan Tiongkok. Sejak masa itu, cikal bakal ibukota Indonesia ini telah mengenal perbedaan, bahkan pembauran etnis dan ras ini terekam hingga melahirkan identitas suku yang baru, yang dikenal sebagai suku Betawi.
Istilah mestizo pun menyeruak untuk memahami etnis Betawi, sebab karakternya menggambarkan campuran budaya dari berbagai etnis. Fakta-fakta di atas turut menegaskan bahwa sejak awal kemunculannya, Jakarta sudah menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Berbagai suku di Indonesia dan budaya Arab, China, India, dan Portugis berasimilasi sehingga menciptakan warna baru.
Selain itu, melalui indikator bahasa juga dapat terurai fakta bahwa dalam bahasanya terdapat campuran dari berbagai kelompok etnis. Diketahui bahwa sejak abad ke-19 muncul bahasa baru yang terdengar seperti bahasa Melayu Betawi sekarang.
Hal ini diduga oleh Herman Neubronner van der Tuuk seperti dikutip Muhadjir melalui karyanya Dialek Melayu Jakarta Dewasa Ini, “Bahasa yang dipakai di Batavia adalah semacam bahasa Bali rendah. Menurut pendapatnya, bahasa yang terdapat di daerah ini adalah dialek Melayu dengan berbagai unsur, yaitu Bali, Jawa, Sunda, China, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris.”
Hal itulah yang memberikan posisi istimewa bagi Jakarta, semangat toleransi atas diversitas. Hingga rasanya rasanya pantas untuk mendaulat sosok Jakarta menjadi ibukota negeri ini, sebab ia merupakan representasi atas kepulauan Zamrud Khatulistiwa yang kaya budaya. Jakarta adalah titik temu berbagai kultur yang menawarkan pesona eksotisme Asia.
Selain pesona keragaman kultur, Jakarta pun pernah terkenal dengan julukan Ratu dari Timur atau Koningin van het Oosten pada abad ke-18.
Hal ini dikarenakan kecantikan bangunan dan ramainya perdagangan yang terjalin di dalamnya.
Namun, kini sisa-sisa bangunan itu hampir tergerus oleh pesatnya pembangunan atas nama modernisasi. Jakarta seolah berusaha ‘melupakan’ masa lalu pahitnya karena era kolonialisasi.
Sebuah pertanyaan pun terbersit, “Apakah harus melupakan masa lalu yang kelam?” Jawaban bijak pun tersurat dari ungkapan seorang planner, “Sebuah kota tanpa bangunan tua ibarat lelaki tanpa sebuah memori.”
Bukankah sudah semestinya apabila prinsip itu dipegang teguh untuk memberikan jiwa bagi sebuah kota. Rangkaian memori, entah suka entah duka, menjadi fundamental untuk diceritakan ulang bagi generasi selanjutnya dan memahami bagaimana karakter yang menaungi sebuah kota tercipta.
Dalam buku berjudul Historical Sites of Jakarta karangan Adolf Heuken SJ, ada opini dari Goenawan Mohammad dan Sarwono Kusumaatmadja, keduanya menceritakan kekhawatiran terhadap penduduk Jakarta yang kehilangan ikatan emosional terhadap ibukota.
Menurut Goenawan, “Ribuan orang berusaha mencari penghasilan di Jakarta, tetapi tidak merasakan 'rumah' di kota ini. Mereka tinggal di Jakarta, tetapi tidak mencintai kota ini, karena tak banyak tersisa hal unik dan spesifik, indah atau artistik.”
Maka, Jakarta pun membenahi diri meski nampak lamban tersadar, sebab masih ada warisan sejarah yang dapat diabadikan.
Adolf menyentil pembacanya, di dalam bukunya tersebut ia berujar, “Ini adalah harapan kita bersama (meski kecil) bahwa buku ini mungkin membantu aksi vandalisme dengan memberikan pengetahuan sejarah. Karena 'die vergangenheit nicht kennen (wollen), heisset sich selbst nicht begreifen (wollen). – Seseorang yang tidak (ingin untuk) mengetahui masa lalu, tidak (ingin untuk) memahami dirinya.' (Ahli Sejarah, Raul Hilpert). Jika ini benar, maka kita harus bertanya pada diri kita: mengapa orang-orang tidak peduli untuk mengenal masa lalu dan dirinya sendiri?”
Berkaca pada pendapat tersebut, kita akan memahami betapa esensialnya masa lalu (sejarah). Masa lalu adalah jiwa.
Adolf kembali mengutarakan jika sebuah kota yang penduduknya tidak mengetahui dan menghargai historinya – genius loci – sesungguhnya tidak memiliki penduduk. Kota itu dihuni oleh gerombolan yang berusaha bertahan, untuk mencari keuntungan. Sejarah faktual yang dimiliki sebuah kota membentuk satu elemen pada identitasnya. “Dengan demikian, berbicara tentang identitas orang tanpa mengacu pada sejarahnya, adalah nonsense,” ungkap Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Maka adalah tugas kita bersama untuk mengembuskan kembali jiwa bagi Jakarta.
Kita harus tidak rela jika Jakarta kehilangan identitasnya. Kita wajib siaga menjaga warisan sejarahnya, termasuk budaya yang dimilikinya.
Dan, satu hal yang telah mendasari ibukota semenjak kelahirannya ialah napas diversitas yang wajib diapresiasi.
Sebab Jakarta yang kosmopolitan memperoleh identitasnya melalui sejarahnya sebagai kota pelabuhan.
Melintasi waktu berabad-abad lamanya, latar perbedaan senantiasa hadir mengikuti perubahan zaman.
Kota yang pernah dinamai Batavia ini pun tak pernah bosan bercengkerama dengan keragaman.
Perbedaan baginya bukanlah jurang, melainkan jembatan untuk menampilkan pesonanya.
Sebagai ibu kota, seyogianya Jakarta menjadi suri teladan bagi kota-kota lainnya dalam pembangunan dan toleransi.
Hal itu dibenarkan oleh pakar sosiologi perkotaan, Dr. Linda Darmajanti, M.T., “Di kota besar, hampir tidak ada masyarakat yang homogen. Kita beragam dan tidak seragam, justru itu kita harus memelihara toleransi. Diversitas adalah hal yang wajar di kota metropolitan.”
Kemudian ia melanjutkan, “Sebagai masyarakat urban, kita harus memiliki partisipasi sosial untuk memelihara kota dan turut menegakkan nilai-nilai modern. Warga Jakarta harus siap disiplin, siap dengan keterbatasan lahan, dan juga siap menggunakan transportasi publik. Kita juga harus memiliki kesadaran membangun peradaban kota, yang ujungnya akan membuat hidup sejahtera dan tenteram.”
Selain itu, ia juga mengingatkan kembali, bahwa sebagai masyarakat modern, kita harus berpikir rasional, bukan mengutamakan emosional. Sebab semakin tinggi peradaban, semakin tinggi pula rasionalitas.
Maka di masa ini, Jakarta juga pun terdepan untuk memenuhi hasrat para generasi muda sebagai pusat kreativitas.
Di kota ini, Anda akan menemui multifungsi peran kota, ia menjadi pusat kebudayaan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, termasuk berperan sebagai ibu kota.
Elemen estetika juga tersaji dalam bentuk fashion dan seni sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam keseharian penduduknya. Di kota ini, jukstaposisi tampil kentara. Elemen tradisional dapat berjalan seirama dengan elemen modern, seirama dengan terbukanya tangan Jakarta pada hal-hal baru, sebab begitulah sikap masyarakat perkotaan.
Jakarta juga tengah berbenah di bidang pembangunan dalam rangka bersiap untuk merekam jejak-jejak baru di masa depan. Jakarta berusaha memikat kita untuk kembali jatuh cinta padanya yang pernah menjadi Ratu dari Timur.
(Foto: Courtesy of Hermawan Tanzil)