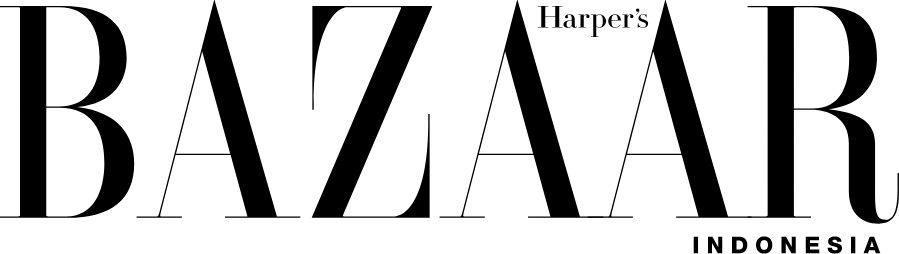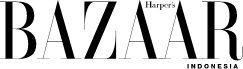Jika Anda pernah menonton sinema-sinema bertema fashion, apalagi jika berkisah biografi perancang busana ternama, ada hal-hal baru yang terungkap.
Misalnya, ketika saya menyaksikan film berjudul Yves Saint Laurent yang bercerita tentang sosok perancang busana yang pernah bergabung dengan rumah mode Christian Dior.
Kisah itu tak hanya berada di arena kehidupan pribadinya, bahkan lebih luas lagi, para penikmat sinema seolah diajak mengetahui dunia di balik layar sebuah pementasan mode, yang kita kenal dengan sebutan fashion show. Sehingga membuka tirai yang selama ini menutupi proses yang dikerjakan sebuah label busana sebelum model berjalan di atas panggung.
Faktanya tak hanya mendesain, sebuah rumah mode juga harus mempersiapkan peragaan busana, mengundang tamu, bahkan menentukan siapa yang layak didaulat menempati barisan tempat duduk pertama, atau kita kenal dengan istilah front row.
Saya pernah membaca sebuah ulasan tentang front row dari mata seorang PR veteran, Erin Hawker, “Pertama, Anda harus menghitung seberapa banyak kursi yang tersedia di front row.
Kemudian memperkirakan berapa banyak kursi yang akan diberikan untuk pihak media, retail, VIP, dan teman-teman dekat dari brand.”
Ia pun menambahkan, “Sekalipun Anda sudah memutuskannya, selalu saja ada perdebatan internal tentang siapa yang pantas ditempatkan di baris front row,” ungkapnya.
Baca juga: Apa Perbedaan Antara Fashion Blogger dan Influencer?
Lantas, mengapa nampak begitu penting masalah front row ini? Sebab nyatanya, ada bahasa yang tak terucap dari barisan pertama.
Ada hierarki dan status sosial yang melekat pada mereka yang mendapat kesempatan berada di sana.
Bahkan, terkadang harta kekayaan pun belum tentu dapat mengantarkan Anda untuk duduk di barisan ini.
Satu hal yang pasti, mereka yang tak pernah terpinggirkan dari deretan pertama adalah para editor fashion ternama, pemimpin redaksi majalah mode yang mendunia, clientele (yang pastinya adalah klien setia yang memiliki ikatan emosional dengan sang perancang, klien yang selalu datang untuk memercayakan busananya pada label itu), sekelompok buyer (tentu saja tak sembarang profesi buyer, hanya mereka yang mendatangkan banyak keuntungan berhak turut mengurasi karya yang akan ditampilkan untuk dipajang di department store atau butiknya), dan selebriti atau public figure (yang lagi-lagi haruslah punya hubungan baik dengan label yang bersangkutan).
Faktanya, semakin penting seseorang, akan semakin dekat pula posisi duduknya dengan panggung.
Tempat duduk Anda juga menyatakan (secara tak tertulis atau lisan) arti Anda di mata rumah mode tersebut, dan tentu saja sebuah tolak ukur seberapa penting majalah/asosiasi yang Anda wakili.
Seiring berkembangnya zaman, turut diikuti perkembangan teknologi, maka penghuni tetap front row pun kedatangan tetangga baru, mereka yang disebut Suzy Menkes sebagai peacocks (coba lihat penampilan mereka yang selalu memukau dari ujung kepala hingga ujung kaki, terkadang inspirasional, dan di lain waktu membutuhkan waktu untuk mencernanya).
Mereka adalah kelompok fashion bloggers yang dilahirkan oleh kemajuan teknologi dan derasnya informasi.
Sehingga kurang lebih sekitar sepuluh tahun lalu, datanglah generasi muda ini dan memperoleh bangkunya di deretan terdepan bersama crème de la crème dunia mode.
Ledakan populasi mereka dimulai dengan tren blog tentang street style, yang memperlihatkan kepiawaian orang-orang ini dalam memadupadankan busana dan menawarkan gaya yang segar, dengan tujuan ditangkap para fotografer yang mengabadikan street style ke dalam blog-nya.
Hingga fenomena ini dituliskan Suzy Menkes dalam artikelnya, bahwa pekan mode bertransformasi menjadi celebrity circus, kumpulan orang-orang yang terkenal karena being famous.
Dampak berikutnya adalah munculnya kesadaran dari pihak label tersebut betapa kuatnya pengaruh fashion bloggers, khususnya ketika apa yang mereka kenakan dapat menggiring khalayak untuk membeli koleksi busana yang mereka sajikan ke publik.
Contohnya di tahun 2008, Marc Jacobs menamakan sebuah karya tasnya dari nama seorang fashion blogger, Bryanboy.
Sehingga, terbentuklah hubungan simbiosis mutualisme antara label dan fashion bloggers, sederet rumah mode berbondong-bondong memberikan produk mereka secara cuma-cuma agar dipakai para blogger dan difitur di dalam blog mereka.
Bahkan, turut tercipta kolaborasi antara keduanya seperti kolaborasi Man Repeller dengan Gryphon, From Me to You dengan Tiffany, dan Veuve Clicquot dengan Oscar de la Renta.
Hal itu sah-sah saja, pasalnya kerja sama kedua belah pihak terjadi secara natural, fashion bloggers perlu pendapatan, dan brand juga membutuhkan peningkatan konsumen (atau review yang baik).
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kelayakan mereka memperoleh posisi di baris pertama peragaan busana.
Apakah perlu menempatkan mereka di barisan depan?
Nyatanya, beberapa brand memang memiliki alasan masing-masing, toh akhirnya front row tak hanya menambah fungsinya, tak lagi sekadar sarana para editor fashion mengurasi karya desainer (dan sesekali tatapan menghakimi) tetapi juga menjadi tempat “menjual” produknya melalui jepretan kamera atau gadget para fashion bloggers yang secepat kilat mengunggah foto-fotonya saat pergelaran busana berlangsung.
Namun, tentu saja bukan masalah kecepatan informasi saja yang bisa dijadikan alasan mereka dapat menempati front row.
Apakah orang-orang yang tenar tanpa proses ini memiliki latar belakang yang tepat untuk memberikan komentar tentang fashion?
Jika kita bandingkan dengan kuli tinta publikasi mode, mereka memang bergelut dengan fashion di kesehariannya, dan mereka memulai kariernya dari bawah, dan tentu saja dilengkapi amunisi pengetahuan fashion yang semestinya.
Sebuah isu dan fenomena menjadi semakin menarik jika diiringi pro dan kontra, sama halnya dengan posisi fashion bloggers di front row.
Seorang fashion blogger asal Singapura, Alvin Cher (bagaholicsboy) mengungkapkan opininya, “Saya menghargai setiap pergelaran busana, sudah pada tempatnya jika ada hierarki pada posisi duduk. Jika diserahkan kepada saya, pemimpin redaksi majalah mode akan saya tempatkan di front row, deputy dan editor fashion di baris kedua, dan kalau beruntung, fashion bloggers di deretan ketiga.
Layak dihormati, tanpa embel-embel drama. Burberry melakukan hal ini, begitu juga Chanel. Jadi mengapa yang lain tidak?”
Sedangkan, Maya Roswita Wahyuningtias, mantan praktisi dunia retail di Indonesia, mengemukakan pendapat berbeda, “Sehubungan dengan berkembangnya media digital di dunia, tidak menjadi masalah menempatkan fashion bloggers di front row asalkan benar-benar yang internationally super famous!”
Konklusinya, fashion bloggers berhak untuk menempati singgasana front row asalkan mereka memiliki kapabilitas dan power yang sama dengan orang-orang di sampingnya.
Maksudnya adalah, kapabilitas mereka dalam menerjemahkan busana yang mereka saksikan ke dalam tulisan yang mendidik sama halnya dengan para editor yang mampu berbagi pengetahuannya dalam sudut pandang jurnalistik.
Dan di sisi lain, fashion bloggers juga patut memiliki power untuk mendatangkan banyak konsumen bagi label yang bersangkutan.
(Foto: Courtesy of Chanel, Instagram @harpersbazaarus)